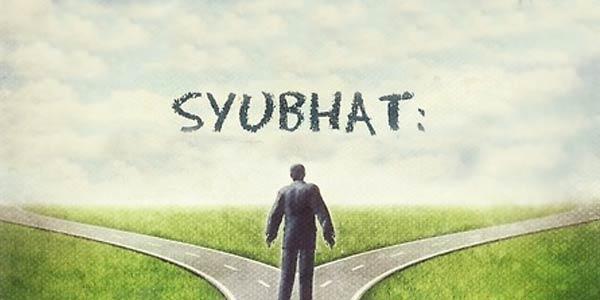"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram juga sangat jelas. Diantara keduanya adalah perkara-perkara mutasyabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang mampu menghindarkan dirinya dari perkara-perkara mutasyabihat, niscaya terjagalah agama dan kehormatannya."
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
Dari 'Amir dituturkan, bahwasanya ia berkata, "Saya pernah mendengar Nuqman bin Basyiir berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram juga sangat jelas. Diantara keduanya adalah perkara-perkara mutasyabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang mampu menghindarkan dirinya dari perkara-perkara mutasyabihat, niscaya terjagalah agama dan kehormatannya. Siapa saja yang terjatuh dalam perkara mutasyabihat, sesungguhnya ia seperti seorang penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar hima (kebun yang terlarang); dan hampir-hampir memasukinya. Ingatlah, sesungguhnya semua yang ada pemiliknya adalah hima (daerah yang terlarang). Ingatlah, hima Allah di muka bumi ini adalah semua perkara yang diharamkanNya. Dan perhatikanlah, di dalam jasad ini ada segumpal darah. Jika ia baik, maka seluruh tubuh juga akan menjadi baik. Sebaliknya, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ingatlah, segumpal darah itu adalah qalbu". [HR. Bukhari dan Muslim]
Di dalam Syarah al-Nawawiy 'Ala Shahih Muslim, Imam Nawawiy menyatakan, "Para ulama sepakat mengenai keagungan dan banyaknya faedah yang bisa diambil dari hadits ini. Hadits ini termasuk salah satu hadits yang menjadi midaar al-Islaam (pilar Islam). Bahkan, mayoritas 'ulama berpendapat, hadits ini merupakan 1/3 Islam. Menurut mereka, Islam itu berdiri di atas hadits ini dan dua hadits lain, yakni, hadits "amal tergantung dari niatnya" dan hadits ""Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat." Sedangkan menurut Abu Dawud al-Syakhtiyani, pilar Islam itu dibangun di atas empat hadits; tiga hadits tadi, di tambah hadits "Pada hakekatnya tidak beriman diantara kalian, hingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri". Menurut para 'ulama, faktor yang menjadikan Nabi saw memiliki kedudukan yang agung adalah; karena beliau senantiasa memperhatikan kesucian dan kehalalan makanan, minuman, dan pakaian. Beliau saw juga selalu meninggalkan perkara-perkara syubhat, sehingga, terjagalah agama dan kehormatannya. Atas dasar itu, beliau saw memperingatkan agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara syubhat. Peringatan ini sangatlah jelas, dengan memtamsilkan perkara syubhat dengan himay (kebun larangan). Setelah itu, beliau menjelaskan perkara yang sangat penting, yakni, menjaga hati…".[Imam Nawawiy, Syarah al-Nawawiy 'Ala Shahih Muslim, juz 11/27]
Pada dasarnya, ada perkara-perkara yang hukumnya sangat jelas dan tidak membutuhkan lagi penjelasan. Sebab, dalil-dalil yang mengharamkan atau menghalalkan perkara tersebut sangat jelas dan tidak samar. Ada pula perkara yang hukumnya belum jelas benar, dikarenakan dalil-dalilnya mengandung banyak pengertian. Untuk itu, sebagian besar ulama membagi urusan manusia menjadi tiga. Pertama, urusan yang kehalalannya sangat jelas. Kedua, urusan yang keharamannya sangat jelas. Ketiga, urusan yang masih samar, apakah halal atau haram, sehingga, tidak banyak orang yang memahami hukumnya, kecuali sangat sedikit. [Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asaqalaaniy, Fath al-Baariy, juz 4/190, Imam Mubarakfuriy, Tuhfat al-Ahwadziy, juz 4/231; Mohammad Syams al-Haq, 'Aun al-Ma'bud, juz 9/127]
Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalaaniy, makna "al-halaal bayyin wa al-haraam bayyin" adalah, kehalalan perkara itu tidak lagi membutuhkan penjelasan, dan setiap orang pasti memiliki persepsi hukum yang sama. Sedangkan di luar perkara tersebut adalah perkara mutasyabihaat. Sebab, perkara itu masih samar, dan tidak banyak orang yang memahami apakah ia halal atau haram. [Al-Hafidz, Fath al-Baariy, juz 4/190]
Di dalam Kitab Aun al-Ma'buud dinyatakan; hukum syariat dibagi menjadi tiga. Pertama, perkara yang kehalalannya sangat jelas. Kedua, perkara yang keharamannya sangat jelas. Ketiga, perkara mutasyabihat; yaitu, suatu perkara yang belum diketahui apakah ia halal atau haram. Ini didasarkan kenyataan bahwa, kadang-kadang ada perkara yang jelas-jelas diperintahkan oleh Syaari' dengan disertai ancaman jika ditinggalkan. Ada pula perkara yang jelas-jelas dilarang oleh Syaari' dengan disertai ancaman jika dikerjakan. Ada pula perkara yang perintah dan larangannya tidak disebutkan dengan jelas. Pembagian seperti ini juga sesuai dengan pendapat Imam Syaukani. Di dalam Kitab Nail al-Authar, beliau berpendapat, perkara mubah dan makruh termasuk perkara mutasyabihat. [Imam Syams al-Haq, 'Aun al-Ma'buud, juz 9/127]
Ketika memaknai hadits di atas, Imam Nawawiy berpendapat; urusan manusia itu dibagi menjadi tiga. Pertama, ada perkara yang kehalalannya sangat jelas dan tidak samar lagi; seperti roti, buah-buahan, minyak, dan makanan-makanan yang lain. Juga perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas halalnya, misalnya berbicara, melihat, berjalan, serta perbuatan-perbuatan lain yang kehalalannya sangat jelas, dan tak ada sedikitpun keraguan. Kedua, ada pula perkara yang keharamannya sangat jelas. Misalnya, khamer, daging babi, bangkai, dan kencing. Demikian pula zina, berdusta, dan ghibah. Ketiga, ada pula perkara samar yang belum jelas benar, apakah ia halal atau haram. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, dan mereka juga tidak memahami status hukumnya.[Imam Nawawiy, Syarah al-Nawawiy 'Ala Shahih Muslim, juz 11/27]
Definisi Mutasyabihaat
Kata "musyabbihaat", mengikuti wazan mufa''ilat (dengan huruf 'ain di tasydid), bermakna "syubihat bi ghairihaa mimmaa lam yatabayyan bihi hukmuhaa 'ala ta'yiin" (mirip dengan perkara lain yang belum jelas benar hukumnya). Redaksi "musyabbihaat" terdapat di dalam hadits riwayat Imam Muslim. Sedangkan di dalam hadits riwayat Ibnu Majah menggunakan redaksi "musytabihaat", yang maknanya adalah, "mauhidah iktasabat al-syibh min wijhain muta'aaridlain" [bersatunya kesamaran dari dua arah pengertian yang saling bertentangan]. Sedangkan di dalam riwayat al-Daramiy, dari Abu Nu'aim, syaikhnya Imam Bukhari, menggunakan lafadz "mutasyaabihaat".[Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalaaniy, Fath al-Baariy, juz 1/127]
Dalam kamus Lisaan al-Arab, dinyatakan; syabaha – al-syibhu, al-syabahu – al-syabiih bermakna al-mitslu (mirip, atau serupa). Bentuk pluralnya adalah asybaah. Asybaha al-syai`u al-syai`a : maatsalahu (menyerupainya). Bentuk jamak dari syabaha bisa juga masyaabih. Al-Musytabihaat bermakna perkara yang sangat pelik dan sulit (al-umuur al-musykilaat). Al-mutasyaabihaat adalah al-mutamaatsilaat (saling menyerupai). [Imam Ibnu Mandzur, Lisaan al-'Arab, juz 13/503-504]
Menurut Imam Nawawiy, musyabbihaat adalah perkara yang belum jelas benar apakah halal atau haram. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mengetahui perkara itu, dan mereka juga tidak memahami hukumnya. Hanya para ulama yang mampu mengetahui hukumnya berdasarkan nash, qiyas, dan istishhaab. [Imam Mohammad Syams al-Haq, 'Aun al-Ma'buud, juz 9/127] Kesamaran perkara itu disebabkan karena adanya pertentangan dua dalil dan tidak ada satu dalil yang lebih rajih (kuat) dibandingkan dalil yang lain. [al-Hafidz,Fath al-Baariy, juz 1/127]
Imam Al-Shan'aniy, dalam kitab Subul al-Salaam, menyatakan, "perkara musyabbihaat" adalah perkara yang tidak diketahui halal dan haramnya. Akibatnya, perkara itu menjadi samar antara halal dan haram. Banyak orang yang tidak mengetahui perkara itu kecuali para ulama yang mengetahui nash-nash syariat. [Imam al-Shan'aniy, Subul al-Salaam, juz 4/172]
Hukum Menjauhi Perkara-Perkara Syubhat
Hadits di atas berisi perintah untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat. Barangsiapa tidak bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, baik dalam pekerjaan dan penghidupannya, niscaya kehormatan dirinya tidak terpelihara. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa, hadits ini merupakan perintah untuk selalu memelihara urusan-urusan agama dan kehormatan diri. [Al-Hafidz, Fath al-Baariy, juz 1/127] Dengan kata lain, siapa saja yang bisa menjauhi perkara-perkara syubhat, sebelum jelas benar status hukum syariat dalam masalah itu, terjagalah agama dan kehormatan dirinya. [Imam Mohammad Syams al-Haqq, 'Aun al-Ma'buud, juz 9/128]
Hanya saja, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum orang yang mengerjakan perkara-perkara syubhat. Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian ulama berpendapat hukumnya haram. Ada pula yang berpendapat makruh. Ada pula yang tawaqquf (abstain), yakni disamakan dengan perbedaan pendapat pada perkara-perkara yang hukumnya belum dijelaskan oleh syariat. [al-Hafidz Ibnu Hajar, Fath al-Baariy, juz 1/127]
Masih menurut al-Hafidz, syubhat itu terjadi pada empat hal. Pertama, adanya pertentangan dalil, di mana keduanya tidak ada yang lebih rajih. Kedua, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama akibat perbedaan dalil. Ketiga, yang disebut syubhat adalah perkara yang berhukum makruh, karena ada arah yang berlawanan; antara mengerjakan dan meninggalkan. Keempat, perkara mubah. Dalam kondisi seperti ini, perkara-perkara tersebut tidak mungkin bisa ditarjih mana yang lebih kuat. Yang mungkin bisa dilakukan hanyalah menimbang mana yang menyelisihi keutamaan (khilaful aula), berdasarkan pertimbangan lebih baik dikerjakan atau tidak, atau karena pertimbangan-pertimbangan lain.[Ibid, juz 1/127]
Barangkali, penjelasan al-Hafidz Ibnu Hajar ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Qadliy Taqiyyuddin. Di dalam Kitab al-Nidzam al-Ijtimaa'iy, Qadliy Taqiyyuddin menyatakan, syubhat itu terjadi pada tiga keadaan berikut ini.
Pertama, syubhat yang menyangkut hukum atas benda (apakah haram atau mubah) dan perbuatan (apakah berhukum wajib, haram, makruh, sunnah, ataukah mubah). Dalam keadaan seperti ini, status hukum atas benda dan perbuatan itu belum diketahui dengan jelas. Jika seorang mukallaf menghadap syubhat semacam ini, ia tidak boleh melakukan apapun, hingga status hukum atas benda dan perbuatan itu jelas. Jika dugaan kuatnya (ghalabat al-dzann) telah condong pada sebuah hukum yang dianggapnya kuat, barulah ia boleh berbuat berdasarkan dugaannya itu. Ini berlaku baik bagi seorang mujtahid maupun muqallid. Jika dengan ijtihadnya, seorang mujtahid telah condong kepada satu hukum, barulah ia boleh berbuat berdasarkan hukum yang diadopsinya. Demikian pula seorang muqallid. Jika seorang muqallid menyakini pendapat seorang mujtahid lebih kuat, atau jika ia telah mengetahui kredibilitas ilmu dan keadilan dari seorang mujtahid, maka ia boleh mengadopsi hukum yang digali oleh mujtahid tersebut, dan beramal sesuai dengan pendapat itu.
Kedua, syubhat yang dianggap sebagai perbuatan haram, meskipun sebenarnya perbuatan itu mubah, disebabkan begitu dekatnya perbuatan tersebut dengan keharaman. Misalnya, seseorang yang menyimpan hartanya di dalam bank yang melakukan aktivitas riba; seseorang yang menjual anggur kepada pedagang yang memiliki usaha pembuatan khamer; atau seseorang yang mengajar wanita secara privat, baik mingguan atau harian, dan sebagainya. Pada dasarnya, perbuatan-perbuatan itu mubah dan boleh dilakukan oleh setiap orang. Hanya saja, perbuatan-perbuatan tersebut lebih utama untuk ditinggalkan, semata-mata untuk memelihara diri dan bersikap wara‘.
Ketiga, syubhat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap perbuatan mubah, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan haram. Akibatnya, perbuatan mubah tersebut dijauhi karena khawatir terhadap anggapan orang lain yang menggolongkannya ke dalam perbuatan haram. Misalnya, ada orang yang selalu melintasi tempat-tempat maksiyat, misalnya lokalisasi pelacuran, bioskop, perjudian, dan lain-lain. Lantas, banyak orang menyangka dirinya sebagai seorang fasik. Akhirnya, karena khawatir terhadap pendapat orang banyak, ia menjauhkan diri dari perbuatan mubah tadi. Contoh lain adalah seorang suami yang menyuruh istrinya atau mahramnya yang lain untuk menutupi wajahnya dengan cadar. Padahal, ia mengetahui, wajah bukanlah aurat. Tindakan demikian dilakukan semata-mata karena adanya perasaan khawatir terhadap pandangan masyarakat yang menganggap istrinya atau saudara perempuannya telah membuka aurat. Dalam kasus semacam ini, terdapat dua tinjauan:
(1) Perkara yang dianggap oleh masyarakat sebagai perkara haram atau makruh tersebut, secara langsung memang haram atau makruh menurut syariat. Tatkala seseorang melakukan suatu perbuatan mubah yang dianggap masyarakat sebagai perbuatan terlarang, dalam keadaan seperti ini, ia harus memelihara diri dari perkara mubah tersebut karena khawatir atas persangkaan orang terhadap dirinya. Ketentuan semacam ini didasarkan sebuah riwayat dari Ali bin Husain. Beliau menuturkan bahwa, Shafiyyah binti Huyay, salah seorang istri Nabi saw, menyampaikan kabar kepadanya bahwa Shafiyyah mendatangi Rasulullah saw, sementara itu Rasulullah saw sedang i’tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Shafiyyah lantas bercakap-cakap dengan Nabi saw berberapa saat sejak usainya shalat Isya`. Setelah itu, Shafiyyah pulang dengan diantar oleh Rasulullah hingga sampai di pintu masjid, dekat dengan tempatnya Ummu Salamah, istri Nabi saw. Tiba-tiba, dua orang pria dari kalangan Anshar melintas di dekat mereka, seraya mengucapkan salam kepada Nabi saw. Mereka kemudian langsung pergi. Rasulullah saw. berseru kepada mereka berdua, ‘Tinggallah di tempat kalian, sesungguhnya ia adalah Shafiyyah binti Huyay’. Kedua orang pria itu pun terkejut seraya mengucapkan, ‘Mahasuci Allah! Duhai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mengatakan seperti itu’. Nabi saw. kemudian bersabda sebagai berikut, "Sesungguhnya setan memasuki anak Adam melalui peredaran darahnya. Aku khawatir, ia memasuki tubuh kalian berdua".
Arti kata tanqalibu adalah kembali, sehingga kata yuqallibuhâ berarti mengembalikannya. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa Rasulullah saw berusaha menghilangkan syubhat yang ada dalam diri dua orang sahabat beliau, meskipun dalam diri Rasulullah saw tidak mungkin ada syubhat.
- Perkara syubhat yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan dianggap sebagai perbuatan terlarang, padahal pada hakikatnya tidak terlarang. Karena ada kekhawatiran terhadap anggapan masyarakat, akhirnya seseorang menjauhinya karena pendapat masyarakat, bukan karena sesuatu itu terlarang. Dalam kondisi seperti ini, perkara syubhat seperti ini tidak boleh dijauhi, bahkan mestinya tetap dilaksanakan dan dianggap sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Ia tidak perlu memperhatikan pendapat masyarakat. Allah Swt. telah menegur Rasulullah karena perbuatan seperti itu melalui firman-Nya, "Kamu takut kepada manusia, padahal Allahlah yang berhak kamu takuti. (QS al-Ahzaab [33]: 37). Kenyataan ini menunjukkan bahwa, seorang Muslim, jika melihat atau memahami suatu perkara yang tidak dilarang oleh syariat, hendaknya ia melakukan hal itu, meskipun seluruh manusia menganggapnya terlarang. [Qadliy Taqiyyuddin, al-Nidzam al-Ijtimaa'iy, 99-101]
Jika seorang Muslim menjauhi perkara-perkara syubhat yang dilarang oleh syariat, niscaya, kehormatan dan kesucian dirinya akan selalu terpelihara.
Persepsi Salah Terhadap Perkara Syubhat dan Makna Silent Syariah (Syariah Diam)
Perkara syubhat bukanlah perkara yang tidak memiliki status hukum. Sebab, al-Quran dan Sunnah datang untuk menjelaskan dan menerangkan setiap urusan manusia. Al-Quran telah menyatakan masalah ini dengan sangat jelas. Allah swt berfirman;
"dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri".[TQS An Nahl (16) : 89]
"Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan".[TQS Al An'aam (6) : 38]
Ayat-ayat di atas menunjukkan dengan sangat jelas, tak ada satupun masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash-nash syara'. Dengan kata lain, tak ada satupun permasalahan yang tidak memiliki status hukum.
Hanya saja, sebagian orang ada yang beranggapan, di dalam Islam ada perkara-perkara tertentu yang didiamkan oleh syariah, alias tidak dijelaskan hukumnya oleh syariat (silent syariah). Dalam ranah semacam ini, manusia diberi kebebasan untuk menetapkan status hukum atas benda maupun perbuatan. Alasannya, masih menurut mereka, syariat tidak menjelaskan status hukum atas masalah-masalah tersebut.
Riwayat-riwayat itu adalah sebagai berikut;
عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ
"Dari Salman dituturkan, bahwasanya Nabi saw pernah ditanya tentang samin (lemak), keju, dan keledai liar. Beliau saw menjawab, "Halal adalah apa-apa yang Allah halalkan di dalam kitabNya, dan haram adalah apa-apa yang Allah haramkan di dalam kitabNya. Adapun apa-apa yang didiamkan (tidak dijelaskan di dalam Kitab), sesungguhnya hal itu termasuk apa yang dimaafkan ('afwun)".[HR. Imam Turmudziy. Menurut Abu 'Isa, hadits ini gharib]
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
"Dari Ibnu 'Abbas ra dituturkan, bahwasanya ia berkata, "Masyarakat jahiliyyah dahulu ada yang memakan sesuatu, dan mendiamkan sesuatu karena merasa jijik. Lalu, Allah swt mengutus nabiNya saw, dan menurunkan kitabNya. Allah juga menghalalkan apa yang dihalalkannya, dan mengharamkan apa-apa yang diharamkannya. Apa yang dihalalkan Allah, maka ia adalah halal. Apa yang diharamkan Allah, maka ia adalah haram. Sedangkan apa yang didiamkan (tidak dijelaskan hukumnya), maka ia adalah 'afwun. Kemudian, Rasulullah saw membaca firman Allah swt, "Qul laa ajidu fiimaa uuhiya ilayya muharraman.."[HR. Imam Abu Dawud]; dan masih banyak riwayat-riwayat lain yang senada.
Riwayat-riwayat ini sering dijadikan hujjah sekelompok orang untuk menjustifikasi pendapat mereka mengenai silent syariah (syariat diam). Menurut mereka, yang dimaksud silent syariah adalah, diamnya syariah terhadap beberapa perkara. Dengan kata lain, ada beberapa perkara yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syariat, atau, tidak memiliki status hukum. Ada pula yang berpendapat, selama al-Quran tidak menjelaskan kehalalan atau keharaman suatu perkara (benda atau perbuatan), maka perkara tersebut tergolong yang didiamkan (silent syariah), dan secara otomatis berhukum mubah.
Lantas, apa yang dimaksud dengan silent syariah (sukuut syariah) yang sebenarnya? Benarkah ada beberapa perkara yang tidak memiliki status hukum?
Pada dasarnya, tidak ada satupun masalah yang tidak memiliki status hukum, atau tidak dijelaskan hukumnya oleh syariah. Oleh karena itu, pendapat mereka mengenai silent syariah adalah pendapat yang keliru. Sebab, pertama, permasalahan yang didiamkan oleh syariat (silent syariah), bukanlah permasalahan yang tidak memiliki status hukum, akan tetapi ia tetap memiliki status hukum. Menurut Qadliy Taqiyyuddin, hadits ini sama sekali tidak menunjukkan adanya perkara-perkara yang tidak dijelaskan hukumnya oleh Syariat. Hadits ini hanya menunjukkan, adanya perkara-perkara yang tidak diharamkan oleh Allah swt sebagai rahmat bagi kita, dan Allah swt berdiam diri dari pengharamannya. Topik yang dibicarakan oleh hadits ini bukanlah "diam" terhadap pensyariatan hukum atas masalah-masalah tersebut, atau tidak adanya penjelasan hukum atas perkara-perkara tersebut, akan tetapi, diam (sukut) terhadap pengharamannya. Hanya saja, sukuut 'an tahriimihaa (diam terhadap pengharaman suatu perkara), bukan berarti perkara tersebut berhukum mubah, akan tetapi, hanya menunjukkan bahwa perkara tersebut halal. Halal di sini mencakup hukum wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Sebab, empat hukum ini termasuk perkara yang halal.
Namun, ketentuan ini hanya berlaku pada perkara-perkara yang didiamkan itu saja, dan tidak berlaku bagi semua perkara yang tidak dijelaskan oleh syariah. Selain itu, makna dari hadits ini adalah adanya "pemaafan" ('afwun) terhadap masalah-masalah tertentu. Makna semacam ini telah ditunjukkan oleh hadits itu sendiri, dan juga ditunjukkan oleh pecahan kalimat dari hadits-hadits tersebut.; yakni adanya larangan untuk menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, lalu dengan pertanyaan itu, perkara tersebut menjadi haram. Dari Ibnu 'Abbas ra diriwayatkan, bahwasanya beliau berkata, "Dan apa yang tidak disebutkan di dalam al-Quran, maka hal itu termasuk apa-apa yang dimaafkan Allah swt". Hadits ini disebutkan oleh Imam Syatibiy di dalam kitab al-Muwafaqat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam Mushannifnya, bahwa Ibrahim bin Sa'ad pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas, "Apa yang mesti diambil dari harta-harta ahlu dzimmah? Ibnu 'Abbas ra menjawab, 'Al-'Afwu ".
Imam Thabariy juga menuturkan sebuah hadits di dalam tafsirnya dari 'Ubaid bin 'Umair, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan dan mengharamkan. Apa yang dihalalkan Allah, maka halalkanlah. Sedangkan apa yang diharamkanNya, maka jauhilah. Selain itu, ada perkara yang tidak dihalalkan atau diharamkan oleh Allah swt. Yang demikian itu adalah 'afw (pemaafan) dari Allah swt". Atas dasar itu, Nabi saw tidak suka orang yang terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang tidak dijelaskan hukumnya secara jelas. Di dalam sebuah riwayat dari Nabi saw, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan disia-siakan, dan telah menggariskan beberapa ketetapan, jangan dilampaui; dan Allah mengharamkan beberapa larangan, maka janganlah dilanggar, serta mendiamkan beberapa perkara bukan karena lupa untuk menjadi rahmat bagimu, maka janganlah dibahas-bahas lagi."[Lihat Sayyid Saabiq, Fiqih Sunnah, hal, 8] Di dalam riwayat lain juga disebutkan, bahwa Nabi saw bersabda, "Orang yang paling besar dosanya adalah, orang yang menanyakan suatu perkara yang asalnya tidak haram, kemudian menjadi haram dengan sebab pertanyaannya."[HR. Imam Muslim] [Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz 3/23-25]
Dari sini dapat disimpulkan, bahwasanya makna frase "sakata 'an asyya`in" (mendiamkan sesuatu) adalah; Allah swt tidak mengharamkan sesuatu itu, alias menghalalkannya. Hadits-hadits di atas tidak boleh dipahami, ada beberapa perkara yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syariat. Hadits itu harus dipahami, Allah swt tidak mengharamkan perkara tersebut sebagai rahmat bagi kita semua.
Kedua, jika al-Quran tidak menjelaskan kehalalan atau keharaman suatu perkara, bukan berarti secara otomatis perkara tersebut terkategori silent syariah. Sebab, selain al-Quran, Allah swt juga menetapkan sunnah sebagai sumber hukum yang wajib dipatuhi oleh kaum Mukmin. Jika sunnah menjelaskan kehalalan dan keharaman sesuatu, maka perkara tersebut tidak lagi termasuk perkara yang didiamkan oleh syariah. Ini didasarkan kenyataan, bahwa al-Quran kadang-kadang tidak menerangkan suatu masalah dengan rinci. Kadang-kadang ia hanya menjelaskan secara umum atau global saja, sedangkan sunnah menjelaskan secara lebih khusus dan rinci. Oleh karena itu, masalah-masalah yang tidak diterangkan kehalalan dan keharamannya oleh al-Quran secara tegas, bukan berarti perkara tersebut terkategori silent syariah. Selain itu, tidak boleh juga dipahami, jika al-Quran tidak menjelaskan suatu perkara dengan jelas, maka perkara tersebut pasti berhukum mubah.
Sebab, Rasulullah saw memerintahkan kaum Mukmin untuk melakukan ijtihad (proses menggali hukum) untuk menetapkan status hukum masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran dan Sunnah. Di dalam hadits shahih telah dituturkan percakapan Rasulullah saw dengan Muadz bin Jabal, tatkala beliau saw mengutusnya untuk menjadi gubernur Yaman. Beliau saw bertanya kepada Muadz tentang cara menghukumi suatu masalah. Muadz pun menjawab, jika masalah tersebut tidak dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah secara rinci, maka harus dilakukan ijtihad berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi saw. Dari proses ijtihad inilah akan diketahui status hukum atas perkara tersebut. Walhasil, masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara rinci oleh al-Quran dan Sunnah, tidak secara otomatis berhukum mubah.
Keempat, jika makna hadits itu dikaitkan dengan konteks hukum syariat; sesungguhnya, selama seseorang disebut sebagai mukallaf hukum, maka ia wajib terikat dengan hukum syariat pada kondisi apapun. Dalam keadaan semacam ini, maka setiap perbuatan mukallaf harus memiliki status hukum. Sebab, seandainya ada perkara-perkara tertentu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syariah, maka tidak ada lagi taklif hukum pada perkara-perkara tersebut. Padahal, hal ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Pasalnya, khithab taklif itu datang dalam bentuk umum, mencakup setiap persoalan, dan berlaku dalam kondisi apapun. Seorang mukallaf tidak diperbolehkan keluar dari khithab taklif ini. Sebab, ia adalah seorang mukallaf yang wajib terikat dengan taklif (hukum syariat) dalam kondisi apapun.
Seandainya, syariat tidak menjelaskan hukum atas suatu perkara, sama artinya syariat membolehkan seseorang untuk keluar dari khithab taklif. Padahal, hal ini jelas-jelas bathilnya. Dengan demikian, hadits-hadits di atas tidak mungkin dipahami bahwa, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syariat. Akan tetapi, hadits-hadits di atas harus dipahami bahwa, Allah swt berdiam diri dari pengharaman perkara tersebut. Walhasil, perkara tersebut adalah halal.
Kelima, hadits-hadits di atas adalah riwayat ahad yang tidak bisa menentang nash-nash al-Quran yang qath'iy. Seandainya dari sisi riwayat hadits-hadits di atas shahih, dan maknanya memang menunjukkan makna semacam itu –yakni, ada permasalahan yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syariat--, maka hadits-hadits tersebut harus ditolak secara dirayah. Sebab, maknanya bertolak belakang dengan nash-nash yang qath'iy tsubut dan dilalah. Nash-nash qath'iy telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa, syariah diturunkan untuk menjelaskan seluruh permasalahan manusia, dan tidak ada satupun permasalahan yang tidak memiliki hukum, atau tidak dijelaskan hukumnya oleh syariat.
Untuk itu, tidak ada satupun perkara yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syariat. Tidak ada satupun perkara yang tidak memiliki status hukum. Oleh karena itu, tidak ada silent syariah di dalam Islam. Tidak ada satupun perkara yang luput dari hukum syariat.
Oleh : Ustadz Syamsuddin Ramadhan